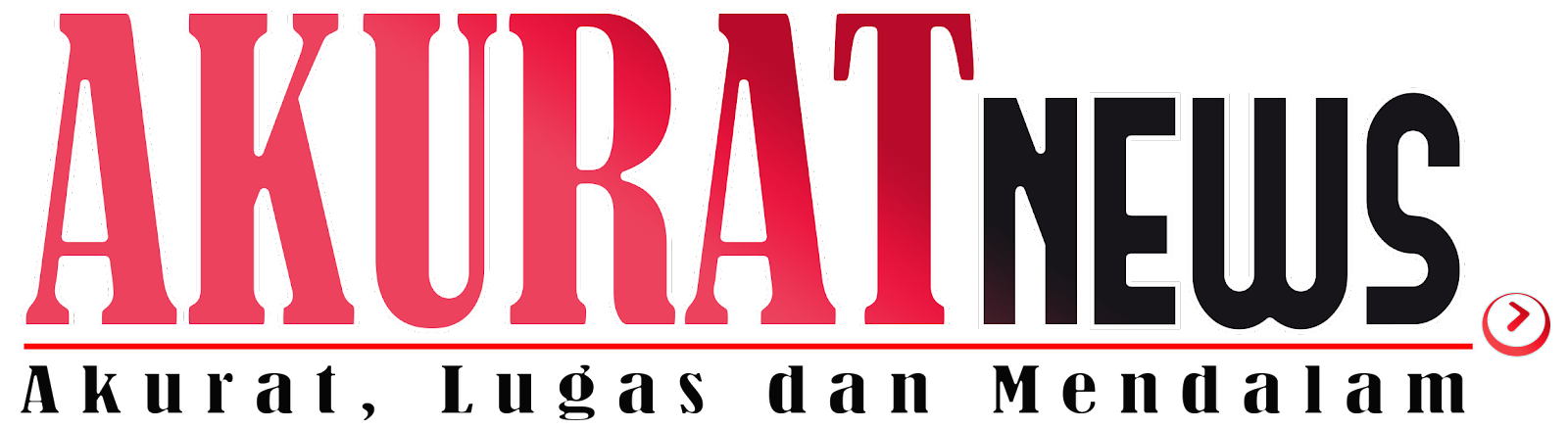Ilustrasi Cover Wanita Suamiku/Ist
Judul: Wanita Suamiku
Penulis: Roy Wijaya
"Kita memang sudah menikah. Tapi jangan harap aku akan
memberikan cintaku."
"Ini hanya sementara, Lin. Tidak lama.” Satya menatap
lamat-lamat perempuan yang baru dinikahinya beberapa jam yang lalu itu. Mereka
tengah duduk di bibir ranjang pengantin yang menguarkan aroma melati. “Aku
minta waktu untuk berusaha membujuk Bunda.”
Sekian detik Lintang terperenyak, tidak menyangka lelaki
dengan tubuh tinggi tegap di hadapannya tega mengatakan hal paling menyakitkan
itu bahkan ketika akad belum lama terucap dari bibirnya.
Gadis berusia jelang dua puluh tiga tahun itu
menggigit-gigit bibir bawahnya, mencoba melerai rasa sesak yang tiba-tiba
membekap dada. Buru-buru ia mengatur napas, mencoba mengendalikan gelombang di
hati yang hampir menyapu daratan. Harum bunga sedap malam yang berada di atas
nakas justru menambah ngilu di hati Lintang. Susah payah ia mendekor kamar
pengantin ternyata berakhir pada sikap sedatar layar monitor yang
dipertontonkan Satya.
“Aku minta waktu bicara pada Bunda. Kita bisa berpisah kalau
Bunda sudah bisa menerima kenyataan kita tidak saling mencintai.”
Lintang menelan ludah. Ia sadar sepenuhnya jika pernikahan
ini hasil perjodohan almarhum ayah Satya dan almarhum ayahnya. Namun, bukan
berarti ia main-main saat melakukannya. Gadis yang belum selesai kuliah itu
sudah bertekad akan belajar menjadi istri yang baik dan tentu saja belajar
mencintai dan menerima Satya.
Lintang berpikir keinginannya untuk meraih cinta Satya akan
bersambut. Sejak tanggal pernikahan ditentukan dan ia tidak mampu lagi
mengelak, Lintang selalu berdoa semoga suaminya kelak akan berusaha menjalani
pernikahan ini dengan baik. Bukankah rasa cinta bisa tumbuh seiring berjalannya
waktu? Keyakinan itulah yang ia genggam kuat-kuat. Namun, ucapan suaminya malam
ini membuat hatinya remuk. Usahanya bertepuk sebelah tangan. Ternyata Satya
memintanya berkorban, bukan berjuang bersama.
“Jadi berapa lama kita akan berpura-pura jadi suami istri,
Mas?” Akhirnya Lintang bisa meloloskan kalimat setelah sekian menit hanya
membisu.
Satya mengalihkan pandangan dari wajah Lintang. Ia menatap
langit-langit kamar, mencoba mengurai pikiran seruwet benang kusut. “Aku tidak
bisa memastikan, Lin. Tergantung kondisi Bunda. Kamu tahu kan, kalau Bunda
punya darah tinggi dan penyakit lainnya. Aku harus hati-hati dan cari waktu
yang tepat untuk bicara dengannya.”
Lintang menarik napas panjang, melepas rasa kecewa yang
menggumpal di dada. Ia merasa telah masuk perangkap manusia paling egois di
dunia. Sejak tadi Satya terus menuntutnya untuk mengerti sementara laki-laki
itu terlihat tidak peduli dengan perasaannya sebagai istri. Kalau pun belum
bisa menganggapnya sebagai istri, minimal menghargai perasaannya sebagai
perempuan. Andai mampu, ia ingin mendaratkan tinju di wajah datar Satya.
“Jadi aku harus menunggu tanpa kepastian?” Lintang tidak
ingin terlihat lemah dan kalah di hadapan Satya. Ia harus memperjuangkan
nasibnya. Ia tidak ingin nasibnya digantung seenaknya. Perempuan bertubuh
semampai itu merasa perlu menyiapkan perasaan ketika mereka benar-benar
berpisah. Tidak mudah menjanda di usia pernikahan yang masih berbilang purnama.
Satya mengganjur napas. Matanya belum beralih dari
langit-langit kamar.
“Membiarkan hubungan seperti ini tanpa kepastian waktu sama
saja dengan menzalimi saya, Mas.” Bola mata bening milik Lintang menatap tajam
Satya. Ia sudah tidak mampu lagi mengerem laju gelombang yang bergulung-gulung
di hatinya.
“Harus ada batas waktu yang pasti. Saya bukan boneka yang
tidak punya perasaan.” Lintang tersekat di ujung kalimat. Susah payah ia
menahan air mata agar jangan sampai tumpah di hadapan manusia dengan hati
sedingin salju kutub utara itu.
“Aku pastikan, tidak lebih dari empat bulan, kamu sudah
bebas. Aku akan segera cari waktu terbaik untuk bicara dengan Bunda.” Akhirnya
Satya memberi keputusan. “Semoga kondisi Bunda stabil,” lanjutnya.
“Kalau dalam waktu empat bulan Mas Satya belum berhasil
membujuk Bunda?”
Satya tertegun. Kemungkinan itu belum pernah ia pikirkan
sebelumnya. Sampai saat ini ia masih yakin suatu hari Bunda akan luluh dan
mengizinkannya menikah dengan perempuan pilihannya.
“A-aku belum memikirkannya, Lin.” Jemari kokoh Satya
menyugar rambut lurus tebal miliknya.
Sesaat pandangan mata Lintang terkunci pada wajah tampan
Satya kala menyugar rambut. Buru-buru ia memalingkan wajah sembari mengingatkan
jika manusia di depannya ini tidak pernah menginginkan pernikahan ini.
“Nanti aku pikirkan lagi kalau sampai empat bulan Bunda
belum juga mengizinkan kita berpisah.”
Lintang membuang napas kasar, lagi-lagi dia yang harus
mengalah. “Baiklah, jika itu maumu,” batin Lintang. Dalam hati, perempuan
berlesung pipit itu berjanji akan menaklukan hati Satya sebelum waktu yang
ditentukan habis. Ia bertekad tidak akan menyerah.
“Okelah, kalau memang itu maunya Mas Satya. Toh memang cinta
nggak bisa dipaksakan.” Lintang berujar sok bijak padahal batinnya merintih.
Satya menarik napas lega. “Terima kasih sudah mengerti,”
ujarnya kemudian. Diam-diam ia salut dengan ketegaran Lintang.
Selama sepekan berada di rumah paman Lintang, Satya
memperlakukan istrinya dengan mesra. Sikapnya di depan semua orang membuat hati
Lintang terus bergetar. Ia khawatir jika waktunya tiba tidak akan sanggup
berpisah dengan lelaki berkaca mata itu.
Namun, jangan ditanya perlakuan Satya di dalam kamar. Lelaki
dengan manik mata sekelam malam itu akan bersikap tak acuh pada Lintang. Ia
bahkan membatasi ranjang dengan guling besar karena di kamar Lintang hanya ada
satu tempat tidur besar. Tak seinchi pun perhatian Satya teralih padanya
membuat Lintang seperti terlempar ke dasar jurang yang gelap.
Genap tujuh hari Satya menikmati cuti demi menjalani
rangkaian prosesi pernikahan yang telah diatur sang bunda. Ia sebenarnya ingin
pernikahan sederhana. Toh nanti mereka akan berpisah juga, jadi tidak perlu
repot-repot menghabiskan banyak uang. Namun, ia tidak kuasa menolak kehendak
bundanya yang telah menyusun rencana dengan matang.
Hari ini Satya bersiap kembali ke Bandung dan Lintang masih
akan tinggal di Yogyakarta untuk menyelesaikan skripsinya yang hampir rampung.
Tiba-tiba, terbit keinginan Lintang untuk melihat-lihat
ponsel Satya, satu hal yang belum pernah dilakukannya selama tujuh hari
bersama. Kebetulan suaminya meninggalkan ponsel di atas nakas saat mandi.
Kamarnya tidak memiliki kamar mandi dalam sehingga Lintang punya cukup waktu
untuk membuka-buka ponsel Satya.
Ia menarik napas lega ketika ponsel Satya tidak bersandi.
Segera dibukanya aplikasi hijau. Ternyata masih terbuka chat dengan seseorang
bernama Hanum. Jemari lentik Lintang segera menyusuri deretan kalimat dalam
chat tersebut.
“Aku sudah bicara dengan Lintang. Hanya tiga bulan dan aku
akan kembali.” Demikian tulis Satya dalam satu chat.
“Kamu sabar ya, Sayang. Tiga bulan tidak lama,” tulis Satya
di chat berikutnya setelah Hanum mempertanyakan berapa lama ia harus menunggu.
Lintang tidak mampu membendung riak-riak di hatinya.
Perlahan sudut matanya mengalirkan luka menyadari takada tempat baginya di
sudut hati Satya. Haruskah ia menjanda di usia muda? Tiba-tiba pertanyaan itu
menjajah perasaannya, menerbitkan rasa risau. Bagaimana ia akan menghadapi
omongan orang ketika waktu perpisahan itu tiba? Tiba-tiba Lintang merasa seolah
bumi tempatnya berpijak terbelah dan menelan tubuhnya. Ia menggelepar dalam
gelap, mencoba meraih cinta yang takpasti. *